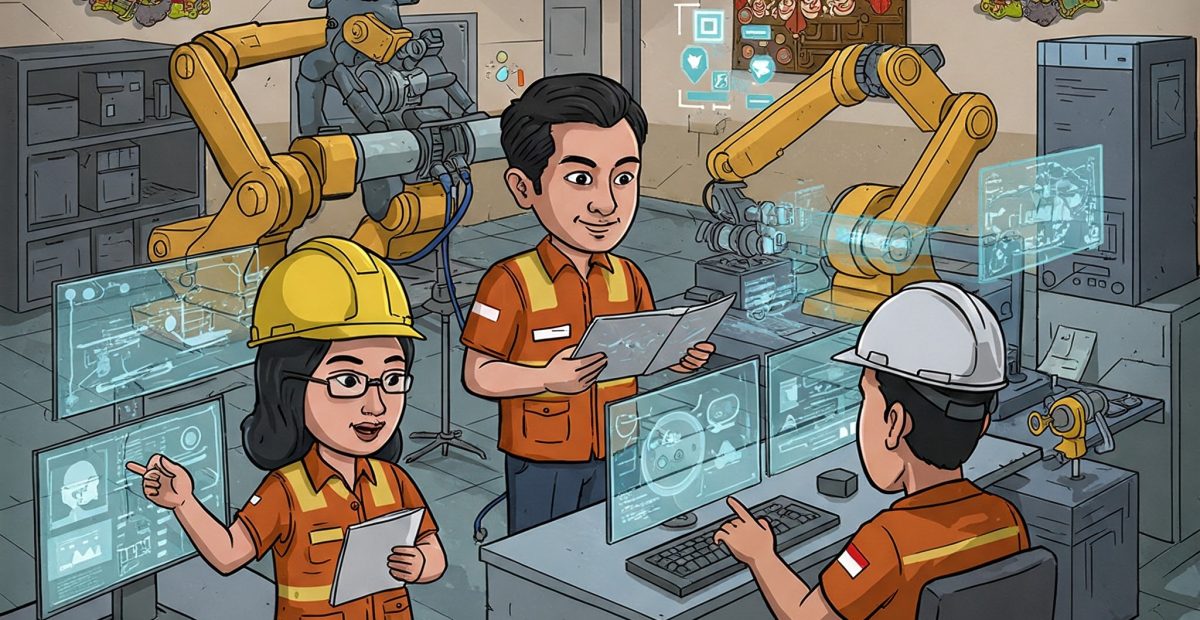Dalam beberapa tahun terakhir, dunia industri global diwarnai dengan munculnya istilah baru: Industry 5.0. Istilah ini seolah menjadi jawaban atas kegelisahan terhadap revolusi industri sebelumnya—Industry 4.0—yang dianggap terlalu fokus pada efisiensi dan otomatisasi. Kini, narasi perkembangan industri mulai bergeser ke arah yang lebih “humanis” yaitu mengembalikan manusia sebagai aktor utama dalam proses industri.
Namun, sebelum kita larut dalam euforia ini, pertanyaannya: apakah konsep Industry 5.0 benar-benar sudah matang, atau hanya sekadar jargon yang lahir terlalu dini?
Apa itu Industry 5.0?
Industry 5.0 sebenarnya muncul bukan karena dorongan teknologi, melainkan sebagai respons kritis terhadap keterbatasan Industry 4.0. Ia juga bukan kelanjutan revolusi industri dalam urutan waktu, tetapi lebih ke pergeseran nilai dan arah tujuan. Industry 5.0 lahir dari refleksi atas kekurangan konsep sebelumnya yang terlalu terpaku pada teknologi sebagai pusat segalanya. Dunia mulai sadar bahwa mengejar otomatisasi tanpa memperhitungkan aspek sosial, lingkungan, dan etika bisa membawa konsekuensi serius: kehilangan pekerjaan massal, ketimpangan digital, hingga eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan.
Sebagai antitesis, Industry 5.0 menempatkan manusia kembali sebagai pusat dari sistem industri. Terdapat tiga prinsip utama dalam pendekatan ini:
- Human-centric: teknologi diciptakan untuk mendukung manusia, bukan menggantikannya.
- Sustainable: aktivitas industri harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan sumber daya alam.
- Resilient: sistem industri harus tahan terhadap guncangan besar, baik itu pandemi, krisis iklim, maupun konflik geopolitik.
Dalam Industry 5.0, manusia tidak digantikan oleh mesin, tetapi justru berkolaborasi dengan teknologi secara cerdas. Misalnya di sektor manufaktur, muncul pendekatan cobot (collaborative robots) yang dirancang bukan untuk mengambil alih pekerjaan manusia sepenuhnya, tetapi untuk membantu tugas-tugas berat atau repetitif, sementara manusia tetap memegang peran dalam pengambilan keputusan strategis, desain, dan inovasi.
Dengan tiga prinsip tersebut, industri masa depan bukan lagi hanya soal kecepatan dan efisiensi produksi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi bisa memberdayakan manusia, menjaga kelestarian alam, dan tetap kokoh saat menghadapi krisis seperti pandemi atau gangguan geopolitik.
Namun, perlu disadari bahwa penerapan Industry 5.0 tidak lepas dari sejumlah tantangan mendasar. Transformasi ini bukan sekadar soal adopsi teknologi canggih, tetapi juga menuntut perubahan paradigma dalam melihat peran manusia dan teknologi di dalam sistem.
Sebagai contoh, dalam program smart farming, penggunaan sensor, drone, dan platform digital memang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian. Namun, dalam kerangka Industry 5.0, keberhasilan tidak cukup diukur dari kecanggihan teknologi semata. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana petani sebagai aktor utama dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mendapatkan akses pelatihan, dan merasakan manfaat ekonomi secara langsung. Dengan kata lain, teknologi harus menjadi alat pemberdayaan, bukan alat pengganti manusia.
Contoh lainnya terlihat di sektor logistik e-commerce, teknologi algoritma rute cerdas memang meningkatkan kecepatan pengiriman. Namun, dalam kerangka Industry 5.0, keberhasilan tidak semata diukur dari kecepatan, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan. Misalnya, opsi pengiriman terjadwal yang mengkonsolidasikan beberapa paket sekaligus dapat mengurangi emisi karbon, sementara perlindungan terhadap kesejahteraan kurir—seperti jam kerja manusiawi dan insentif keselamatan—menjadi indikator penting lainnya. Teknologi harus mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan, bukan sekadar efisiensi.
Kritik dari Para Pakar
Di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan, konsep Industry 5.0 masih memicu diskusi hangat. Sebagian pakar melihatnya sebagai lompatan penting menuju pendekatan industri yang lebih bertanggung jawab dan inklusif. Komisi Eropa, misalnya, sudah mengadopsi Industry 5.0 dalam kerangka kebijakan industri mereka, menekankan hubungan erat antara digitalisasi dan agenda hijau.
Namun tak sedikit pula yang skeptis. Salah satu kritik utama terhadap konsep ini adalah bagaimana Industry 5.0 tampak lebih seperti branding politik ketimbang kerangka ilmiah yang matang. Sejumlah peneliti juga mempertanyakan kedalaman konsep Industry. Apakah ini benar-benar revolusi baru atau hanya rebranding dari ide-ide lama seperti socio-technical systems yang sudah dibahas sejak dekade 1970-an? Bukankah konsep seperti green manufacturing, corporate social responsibility (CSR), atau ekonomi sirkular sudah membahas hal serupa? Selain itu, minimnya kajian ilmiah dan studi kasus lapangan membuat konsep ini belum matang secara metodologis.
Penutup
Gagasan Industry 5.0 mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi seharusnya membawa manfaat bagi manusia, bukan sekadar mengejar efisiensi atau keuntungan semata. Dalam konteks Indonesia, di mana banyak sektor industri masih jauh dari adopsi teknologi tinggi, pendekatan Industry 5.0 mungkin lebih masuk akal karena memungkinkan kita untuk memulai transformasi dari nilai, bukan dari alat. Sehingga mencegah kita jatuh ke dalam jebakan mengejar teknologi demi citra, tanpa memikirkan dampak pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan.
Tantangannya kini adalah menjembatani antara narasi gagasan dan implementasi konkret di industri dan masyarakat. Jika tidak diterjemahkan dengan benar, Industry 5.0 bisa terjebak menjadi jargon kosong tanpa perubahan mendasar, seperti fenomena “greenwashing“—yakni ketika perusahaan menggunakan jargon sustainability hanya sebagai pencitraan semata, namun pada praktiknya masih menerapkan sistem kerja yang eksploitatif.